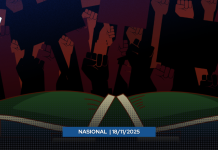Per-bulan Juli 2025, pemerintah mulai menerapkan kebijakan tegas terhadap aset tidak produktif. Negara tidak lagi memberi toleransi bagi warga yang membiarkan asetnya “tidur”. Rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas keuangan selama 3-12 bulan juga otomatis akan dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebijakan ini dibuat karena ditemukan rekening dormant (tidak aktif) yang disalahgunakan dan melanggar hukum. Meskipun dapat mengajukan banding, namun masyarakat menilai bahwa proses nya memakan waktu yang lama dan rumit.
Tak berhenti disitu, Tanah yang dibiarkan kosong tanpa aktivitas selama dua tahun kini berpotensi menjadi milik negara. Pengambilalihan hak milik ini tak hanya terjadi pada tanah yang bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) saja, namun juga Sertifikat Hak Milik (SHM). Langkah ini diambil karena agar tidak ada lahan-lahan terlantar yang nantinya menimbulkan konflik agraria. Lantas, apakah kebijakan ini efektif melindungi masyarakat atau justru merebut hak-hak masyarakat?
Rekening Diblokir Sepihak Tanpa Peringatan, Mengorbankan Rakyat Kecil
Melansir dari Katadata.co.id, PPATK menemukan lebih dari 140 ribu rekening dormant selama lebih dari 10 tahun dengan total uang sebanyak 428,6 Miliar dan sebagian rekening tersebut tidak diperbarui datanya dan dibiarkan terbuka tanpa aktivitas.
Proses pemblokiran ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Beberapa pasal yang menjadi dasar hukum antara lain Pasal 44 ayat (1) yang memberi wewenang PPATK untuk menghentikan sementara transaksi selama maksimal 20 hari kerja. Kemudian, didalam Pasal 44 ayat (2) menyebutkan dalam masa penghentian transaksi tersebut, penyidik wajib menindaklanjuti. Jika tidak, penghentian otomatis batal. Pasal 44 ayat (3) perpanjangan masa penghentian hingga 10 hari kerja jika diperlukan.
Dilansir dari beberapa media, nasabah yang rekeningnya diblokir oleh PPATK sebagian besar tidak dihubungi terlebih dahulu oleh PPATK, sehingga mereka tidak tahu sama sekali saat rekeningnya dibekukan. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menyatakan bahwa seharusnya mekanisme PPATK yaitu memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum terjadi pemblokiran rekening, agar nasabah bisa memberikan pernyataan jika mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online, pencucian uang, dan penipuan. Koordinator Humas PPATK (M. Natsir Kongah) menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan banyak ditemukan di rekening dormant, tetapi tidak ada laporan bahwa nasabah secara aktif dihubungi sebelum pemblokiran dilakukan. Hal inilah yang memantik kekhawatiran masyarakat, Pemblokiran rekening ini dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengancam stabilitas sistem perbankan nasional karena nasabah takut dan memicu penarikan dana besar-besaran dari bank.
Sementara itu, Respon pakar terhadap pemblokiran rekening nasabah itu melanggar HAM. Hal ini karena PPATK dibentuk hanya untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan melakukan pemblokiran rekening nasabah yang merupakan mekanisme pengadilan.
Dampak dari kebijakan ini memengaruhi dari segala bidang. Di bidang ekonomi dan perbankan, nasabah yang rekeningnya terblokir mengalami kerugian karena dana tidak bisa digunakan sementara, dan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan. Di bidang sosial, masyarakat menjadi resah dan khawatir sehingga menarik uangnya dari bank secara massal. Di bidang Hukum dan HAM, Pengawasan yudisial terhadap PPATK dipertanyakan. Akuntabilitas aparat penegak hukum harus ditegakkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Tanah Tak Digarap, Negara Bergerak
Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menyatakan bahwa negara bisa mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Pengambilalihan tanah ini tidak hanya terjadi pada hak atas tanah HGU dan HGB saja, tetapi SHM (Sertifikat Hak Milik), HP (Hak Pakai), HPL (Hak Pengelolaan), dan Tanah hasil dasar penguasaan atas tanah juga dapat diambil alih. Jika melihat dari regulasinya, hukum yang mendasari kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Aturan ini ditandatangani Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 2 Februari 2021. Tanah Terlantar yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) yaitu tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dipelihara. Tanah dengan kriteria tersebut menjadi objek penertiban Tanah Terlantar. Dilansir dari Kompas.com, Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO kebijakan ini dibuat atas dasar keadilan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan hak yang setara.
Melansir dari CNN Indonesia, tanah Bersertifikat SHM dapat diambil alih oleh negara jika tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: Dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; Dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau Fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada. Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dapat menjadi Aser Bank Tanah dan/atau TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara). Pendayagunaan TCUN untuk kepentingan masyarakat melalui: Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional (PSN), Bank Tanah, dan cadangan negara lainnya. Pendayagunaan ini berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, dan/atau Pemerintah Daerah yang memperhatikan kebijakan strategis nasional, rencana tata ruang, dan/atau kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.
Perlindungan atau Pelanggaran HAM Terselubung?
Kebijakan pemblokiran sementara yang dilakukan oleh PPATK dan pengambilalihan Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas properti/harta pribadi terganggu karena pengambilan aset pribadi dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada individu yang bersangkutan tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ini juga mencakup atas hak privasi yang menyiratkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang dan aman khawatir akan ancaman terhadap dirinya atau harta bendanya.
Ketiadaan mekanisme banding/keberatan juga melanggar HAM jika Pemegang Hak tidak diberikan ruang hukum untuk menggugat, menjelaskan, atau meminta waktu proses pengambil alihan tanah. Diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok rentan tetapi secara langsung merugikan kelompok rentan, contohnya pada tanah warisan yang ditinggalkan karena pemilik meninggal dunia dan ahli waria masih di bawah umur, merantau, atau tidak tahu-menahu dan negara bisa menganggap “terlantar” dan mengklaim sehingga menjadi milik negara tanpa sepengetahuan Pemegang Hak atau Ahli waris.
Respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ini cenderung negatif karena masyarakat merasa dipersulit. Seperti hal nya pada kasus pemblokiran rekening, nasabah tidak diberi pemberitahuan sebelum rekening diblokir, proses pembukaan blokir oleh PPATK yang rumit, dan tidak ada transparansi komunikasi kepada nasabah. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap sangat merugikan masyarakat. Bahkan, ketika dalam keadaan darurat tidak bisa diakses. Kebijakan membuat masyarakat merasa khawatir karena pemerintah bisa ambil aset rakyat sesuka hati yang cenderung merugikan rakyat kecil dan juga berspekulasi bahwa kebijakan ini bisa dijadikan celah oleh investor jika tidak dilakukan secara transparan.
Kebijakan yang berjalan tanpa pengawasan publik dan minim transparansi ini menunjukkan gejala otoritarianisme administratif yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah seolah-olah membuat dalih keamanan dan pemberantasan kejahatan sebagai tameng untuk mengintervensi ranah privat rakyat hingga hak kepemilikan dan pengelolaan kekayaan pribadi. Alih-alih membuat publik percaya, kebijakan ini justru memicu rasa khawatir karena membuka peluang pelanggaran hukum. Kini, negara bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai aktor dominan yang mempersempit ruang hidup rakyatnya sendiri. Jika terus dibiarkan, kebijakan yang dipaksakan akan menimbulkan dampak negatif yang semakin merugikan masyarakat hingga melanggar hak asasi atas nama prosedur, serta memicu ketakutan di tengah masyarakat. Sebuah demokrasi tak layak disebut sebagai demokrasi bila suara publik dikebiri dan hak warga dibekap oleh regulasi yang tidak berpihak.
Oleh: Andi Syahrani & Nofiyanti
Editor: Ananda Rizka